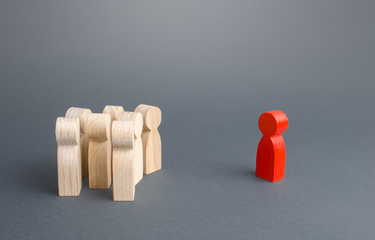 |
| Foto: kompas |
niadilova.wordpress - Peringatan Hari Ibu telah datang lagi. Dan, seperti tahun-tahun sebelumnya, di zaman media sosial (medsos) yang kian menyiksa orang-orang mata manusia ini, orang-orang mengucapkannya dengan antusias di dinding-dinding Facebook mereka. Sebagian yang lain memasang foto-foto lama mereka bersama ibunya, ketika mereka masih kecil atau masih dalam gendongan. Adakah mereka sempat pulang ke rumah ibu mereka? Adakah mereka sempat sungkem dan minta maaf kepada sang bunda? Adakah mereka sempat menelepon ibunda mereka untuk sekedar menyenangkan hatinya? Entahlah.
Dan seperti biasa pula, media sosial adalah tempat untuk menyerakkan kritik, cemooh, dan pelesetan. Banyak yang lucu, tak sedikit yang sinis dan sarkastis, tak terkecuali tentang peringatan Hari Ibu. “Kau kira ibumu punya ipad di kampung?” kata satu kritik; “Kalo bilang selamat Hari Ibu cepat kali mulutmu itu, tiba mamak suruh cuci piring banyak kali ceritamu”, kata kritik yang lain yang bernada Batak. “Ibumu harus dihormati setiap hari, bukan sekali setahun”, kata kritik yang lain lagi.
Memang tiadalah yang terlebih mulia selain ibu, orang yang telah mempertaruhkan jiwa raganya untuk kelangsungan generasi manusia. Saat bayi, ibumu terbangun di malam hari ketika kamu pipis dan berak dalam popokmu, atau ketika kamu haus minta mimik, sementara bapakmu masih asik main domino atau mengocok kertas koa di lepau-lepau kopi sambil ‘mengukir dunia’ dan maota tidak berkeruncingan kian kemari. Namun, dalam kenyataannya seorang ibu masih sering mendapat perlakuan yang tidak sepatutnya, baik dari anak(-anak)nya maupun oleh masyarakat pada umumnya.
Banyak cerita sudah diperdengarkan kepada kita, malah sejak masih lagi di usia kanak-kanak, tentang pentingnya menghormati sosok ibu. Orang Minangkabau diajari tentang perlunya menghormati ibu melalui kisah Malin Kundang yang durhaka kepada Ibunya. Kutukan sang ibu telah mengubahnya jadi batu di Pantai Air Manis. Jika hati ibumu engkau lukai, jika seorang anak sudah berlaku kasar kepada ibunya, yang membuat air mata sang ibu titik dan hatinya pun sedih, maka tiada harapan lagi bagi si anak untuk dapat menjejakkan kaki di pintu sorga.
Cerita Malin Kundang mungkin sebuah iktibar yang sengaja dibuat untuk orang Minangkabau yang mengamalkan sistem matrilineal dan, karena itu, sudah semestinya menghormati dan menjunjung tinggi sosok ibu dalam kehidupan mereka. Di negeri bernasab[1] ibu ini, cerita tentang anak yang durhaka kepada ibunya itu dihadirkan agar sesiapa saja selalu diingatkan untuk menghormati dan menjaga marwah sang bunda. Namun, dalam kenyataannya masih banyak orang yang mengabaikan pesan moral cerita ini.
Cerita Malin Kundang jelas tidak datang dari langit lalu melayang ke Air Manis. Sebuah cerita tidak begitu saja jatuh ke bumi lalu jadi kaba. Malin Kundang adalah protagonis yang merepresentasikan perantau Minang. Ia adalah tokoh yang diciptakan untuk mengingatkan seluruh orang Minang (dulu identik dengan lelaki) yang pergi merantau meninggalkan ranah bunda (homeland) (dengan demikian juga hamba, penulis esai ini). Ia mengandung pesan nyata untuk mereka yang pergi jauh karena dilarikan untung perasaian yang, karena itu, terpaksa meninggalkan ibu (bunda kandung) di kampung halaman, di tepian tempat mandi.
A.A. Navis, dalam cerpennya “Tamu yang Datang di Hari Lebaran” mengingatkan lagi para perantau Minang agar tetap ingat kepada ibu yang mereka tinggalkan di kampung. Sesibuk apapun dirimu di rantau, kirimlah surat atau teleponlah ibumu di kampung. Mendengar suaramu saja, sudah cukup bagi sang ibu untuk mengobati hatinya yang rindu dendam kepadamu, sibiran ulang, obat jerih pelerai demamnya. Jika kau mengirimkan uang belanja untuk ibumu, kirimkanlah uang yang halal, jangan dari uang korupsi. Ingatlah, ketika kecil ibumu memberimu air susunya yang murni, yang putih memancar dari putingnya yang kamu hisap dengan mata jernihmu yang merem melek, yang kemudian menjalari segenap urat darah di sekujur tubuh merah-sucimu. Tapi Navis sebenarnya ingin berpesan lebih jauh lagi: kamu akan menyesal bila orang tuamu keburu meninggal, sementara ketika hidup kamu abai terhadapnya, jarang mengunjunginya. Sering-seringlah mengunjungi orang tuamu selagi mereka masih hidup.
Tapi, apa arti kasih sayang kepada ibumu jika ranah bunda (tanah airmu/daerah asalmu) kau sia-siakan? Tiada sempurna makna kasih kepada ibumu jika Ranah Minangkabau kau ciritkan, kau caci-maki dengan kata-kata yang begitu kotor. Kau tiru kulikat Hanafi, tokoh utama roman Salah Asuhan itu. Dianggapnya dirinya sudah jadi Barat, walau belum pernah menginjak ‘Tanah Dingin’ itu. Baru mengenal wanita Eropa seperti Corrie, sudah tak hendak dia kepada gadis Minang, Rafiah, yang elok budi itu. Hanafi lupa pada akar budayanya, lupa pada tradisinya, lupa kepada asal-usulnya. Abdul Muis, sang pengarang, menyentil orang-orang yang lupa akan budaya dan ranah bundanya sendiri, tempat bunda kandungnya dilahirkan, tempat air tulang ibunya (terima kasih Zelfeni Wimra!) merembes membasahi tubuhnya, yang kemudian melipatgandakan jumlah sel di tubuhnya, membesarkan dirinya. Abdul Muis menyentil mereka yang mabuk modern dan gila Barat, dan lupa pada akar budaya sendiri.
Banyak orang Minang yang berlaku seperti Hanafi. Mereka pergi merantau, lalu merasa sudah modern, merasa adat resam di kampung halamannya sudah ketinggalan zaman, sudah kuno dan tak terpakai lagi. Mereka terjangkit xenocentrism,[2] melihat semua yang ada di luar, lebih-lebih yang membawa ciri kemodernan, lebih super, lebih unggul. Mereka berpikiran bahwa adat Minangkabau harus ditinggalkan, dimusnahkan. Mereka tidak sadar bahwa Barat yang mereka puja-puja sendiri sebenarnya malah lebih konservatif dan selalu mempertahankan nilai budaya mereka (European values) yang selalu dipaksakan kepada bangsa-bangsa lain untuk menerimanya.
Demikianlah, seperti halnya Hanafi, Muhamad Radjab juga jadi ‘murtad’ ketika sudah sukses di rantau. Ketika melawat ke Minangkabau selepas Indonesia merdeka, setelah lama tinggal di Jakarta yang glamour dan ‘modern’ itu, ia melihat semua yang ada di kampungnya dengan pandangan serba negatif, seperti dapat dibaca dalam laporan jurnalistiknya, Tjatatan di Sumatera (Jakarta: Balai Pustaka, 1949). Semuanya buruk dalam pandangannya: kehidupan dalam rumah gadang, pendidikan orang Minang, perekonomian dan pasar, ninik mamak, … . Pokoknya, apa yang tampak olehnya di Sumatera Barat tak ada yang baik. Ia juga mengeritik lagu-lagu Minang yang melankolis dan cenderung berhiba-hiba itu.
Radjab memandang dirinya sudah tinggi benar. Betul ia orang terpelajar, tapi jangan memandang rendah orang kampung. Dalam kehidupan manusia yang paling sederhana pun ada kearifan. Tapi semua orang di kampung dianggapnya kolot. “Apakah jang diketahui [oleh para penghulu] tentang pelbagai expressi dari kehidupan sosial, seperti nisbah-nisbah perekonomian, kesusilan, hukum, ilmu modern, kesenian dan filsafat di Minangkabau saja? Djika tidak diketahuinja selengkapnja dasar-dasarnja djuga tidak […]. Bagaimanakah dapat diharapkan Minangkabau akan lebih madju […] bila kepala-kepala sukunja [hidup] dalam kegelapan selalu, sedangkan bangsa-bangsa lain sudah memasuki tjahaja ilmu jang menjinari seluruh masjarakatnja?”, kata anak tepian Danau Singkarak itu. Karena sudah merasa intelek dan maju, ia menempatkan dirinya di atas gunung tinggi, dan memandang para penghulu yang buta huruf itu bodoh. Ia telah lupa pada dirinya sendiri, sebagai mana pada baberapa tahun sebelumnya ia catat dalam otobiografinya, Semasa kecil di kampung, 1913-1928… . Ia ‘mengencingi’ kepala mamak–mamak dan datuk–datuk-nya sendiri.
Dan kini, hamba yakin masih banyak lagi ‘Malin Kundang’, ‘Hanafi’, dan ‘Radjab’, baik di kampung maupun di rantau. Malah sebagian sudah menjadi ‘maling kondang’, kata penyair Syarifuddin Arifin. Tapi hamba juga tahu, banyak orang Minangkabau terpelajar yang menghargai budaya dan adat resam ranah bundanya, sama halnya seperti dia menyayangi ibunya. Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya, sebab, seperti kata Adi Negoro di tahun 1930, “Bangsa jang tidak memoeliakan kultuuurnja, bangsa itoelah jang akan toeroen harganja dari bangsa jang lain-lain.” (Pandji Poestaka No.2, Thn. VIII, 7 Januari 1930:19 [Dari Djawa Tengah]).
Jadi, apa pun jenis pekerjaanmu – politikus, dosen, pedagang gedang ber-uang berkambut, wartawan, sastrawan (muda), agamawan, aktivis … – tunjukkanlah respek dan baktimu kepada ranah bundamu, dengan caramu sendiri: dengan ujung penamu, dengan kepeng banyakmu, dengan ucapanmu… . Lindungi ranah bundamu seperti kau melindungi ibumu sendiri. Jika kau ikut-ikutan menghancurkan ranah bunda-tepian tempat mandimu (masyarakatnya, budayanya, alamnya), berarti kau bermental Malin Kundang. Terkutuklah kau! Jadi batulah kau! Sekarang kini nangko juga!
Suryadi Sunuri
Leiden, Desember 2015
* Esai ini diterbitkan di harian Padang Ekspres (lembaran ‘Cagak’), Minggu, 27 Desember 2015
=======================
Catatan kaki oleh Admin:
[1] Bukan 'Bernasab' tapi 'bersuku' ke Ibu. Orang Minangkabau bernasab ke Ayah.
[2] Xenocentrism merupakan suatu sikap di mana seseorang meremehkan budaya sendiri dan sangat mementingkan budaya asing.(diambil dari tulisan; SUPERIORITAS BUDAYA ASING DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, atau klik DISINI)


.jpg)

.jpg)





Tidak ada komentar:
Posting Komentar